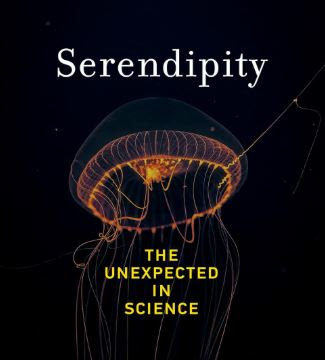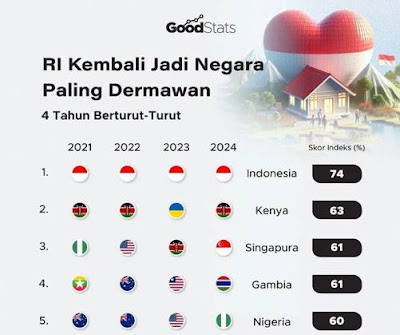Dalam dunia sains yang sering
diasosiasikan dengan experiment yang penuh kalkulasi statistik, hypothesa, dan
metodologi ilmiah yang baku, ada satu elemen yang kerap terlupakan namun justru
kerap menjadi kunci dalam keberhasilan penemuan besar yakni “Serendipitas”. Kata ini,
mengacu pada penemuan yang tidak disengaja namun bermakna, sebagaimana diungkap
dalam buku The Travels and Adventures of Serendipity karya sosiolog Robert
K. Merton dan Elinor Barber.
Bagi Merton, “Serendipity” bukan hanya sekadar kisah keberuntungan yang terjadi dalam
laboratorium, melainkan sebuah konsep sosiologis yang patut disistematisasi.
Esai berikut menyoroti bagaimana Merton, sebagai salah satu founder ilmu sosiologi,
merumuskan serendipitas dalam kerangka yang lebih luas yakni sebagai mekanisme
ilmiah yang memperlihatkan bagaimana struktur sosial, nilai budaya, dan
kebetulan epistemik dapat melahirkan pengetahuan baru secara tak terduga namun tetap
sah secara metode ilmiah.
Jejak
Historis Serendipitas
Asal-usul kata "Serendipity", pertama kali
dipopulerkan oleh Horace Walpole pada abad ke-18, yang terinspirasi dari kisah
tiga pangeran Serendip (dari Sri Lanka). Para pangeran ini selalu beruntung dan
menemukan sesuatu yang tidak mereka cari, kemudian hal itu menjadi sebuah
metafora untuk beberapa penemuan dalam sains, seperti penemuan penisilin oleh Alexander
Fleming, pulsar oleh Jocelyn Bell, gelombang mikro oleh Percy Spencer hingga
obat Viagra yang menunjukkan bagaimana penemuan yang bersifat acak pada hakikatnya tidaklah sepenuhnya “acak”. Ia terjadi dalam konteks intuisi ilmiah, struktur
nilai, dan kemampuan kognitif si peneliti untuk “melihat makna” dari
ketidaksengajaan yang ia lakukan.
Konsep
sebagai Konstruksi Intelektual
Dalam
konteks serendipitas, Merton memperlihatkan bahwa “Penemuan Tak Sengaja” bisa menjadi batu loncatan bagi sains jika
dan hanya jika ada kerangka konseptual tersebut siap untuk menerimanya. Dengan
kata lain, kejutan ilmiah bukanlah semata sebuah “Anugerah”, tetapi juga merupakan ujian kesiapan intelektual. “Chance favors the prepared mind,” kata
Louis Pasteur. Merton sejalan dengan konsep ini, tetapi dengan narasi tambahan, kesempatan juga beroperasi dalam medan sosial yang memediasi makna, legitimasi, dan
tindak lanjut. Dalam hal ini, Merton berbeda dari sosiolog
struktural-fungsionalis lainnya. Ia percaya bahwa kekuatan sains sosial justru
terletak pada kemampuannya merumuskan konsep-konsep yang bisa menjelaskan,
menghubungkan, dan memicu penelitian lintas disiplin.
Tantangan Sistemik: Metodologi yang terlalu kaku, Justru Akan Membunuh
Inovasi
Manuskrip yang ditulis oleh Merton
dan Barber menjadi kritik terhadap mitos positivistik tentang ilmu yang selama
ini dianggap sebagai proyek rasional, linier, dan serba terencana. Keberadaan serendipitas
mendisrupsi narasi ini. Ia membuka celah bukti bahwa ilmu sering bergerak
zig-zag, terantuk oleh kebetulan, dilintasi intuisi, bahkan dipandu oleh error dari sebuah kreasi.
Dengan demikian, serendipitas tidak
membatalkan rasionalitas, tetapi justru melengkapinya. Ia menghadirkan nuansa
dalam dinamika ilmu, bahwa pengetahuan juga lahir dari ruang tak terduga, dari
rekayasa sosial, dan dari kemampuan manusia untuk membaca makna dalam
ketidakteraturan.
Ironisnya, sistem sains modern kerap tidak ramah terhadap serendipitas.
Ketika proposal riset harus memuat roadmap experiment secara rigid, ketika
keberhasilan diukur dari kesesuaian terhadap hypothesa, maka tidak akan ada
lagi tempat bagi hasil experiment yang bersifat anomali. Padahal, penemuan
besar justru sering lahir dari apa yang tampak sebagai “kesalahan”.
Serendipitas membutuhkan ruang untuk gagal, ruang untuk bermain, dan ruang
untuk menyimpang dari rencana awal. Oleh karena itu, reformasi sistem pendanaan
riset perlu mempertimbangkan pentingnya ketidakterdugaan. Bila tidak, kita
hanya akan mencetak peneliti yang hanya mengutamakan efisiensi, namun minim akan inovasi.
Serendipitas
di Era Digital dan Big Data
Sayangnya, satu hal yang terasa
kurang adalah refleksi terhadap relevansi konsep ini di era modern. Dalam
dunia yang terisi oleh big data, machine learning, dan eksplorasi tak
berujung terhadap variabel-variabel tak terduga, keberadaan serendipitas
menjadi semakin relevan. Banyak temuan mutakhir dalam bioinformatika,
astrofisika, dan epidemiologi justru terjadi karena algoritma yang menemukan
korelasi yang tidak dicari oleh ilmuwan di awal hypothesa.
Namun apakah itu masih bisa disebut
“serendipitas”? Jika penemuan acak terjadi melalui mesin, bukan intuisi
manusia, apakah makna sosial dan epistemologisnya masih sama? Inilah
pertanyaan-pertanyaan yang perlu dikembangkan lebih lanjut, dan yang sayangnya saat
ini belum tersentuh dalam beberapa kajian ilmiah.
Menormalisasi Ketidaksengajaan Ilmiah dan
Ekosistem Kolaboratif
Di tengah tuntutan pada linearitas,
output riset yang terukur, dan birokratisasi ilmu yang kian rigid, esai ini mengajak
kita untuk kembali menormalisasi ruang bagi ketidaksengajaan. Bahwa tidak semua
pengetahuan lahir dari hipotesis yang disusun secara rapi. Bahwa dalam dunia
ilmu, sering kali kita menemukan sesuatu yang tak dicari, dan justru
karena itulah ilmu tetap hidup dan berkembang.
Seringkali, kita mengaitkan serendipitas dengan sosok individu yang jenius.
Namun serendipitas, justru sering terjadi dalam jejaring sosial, yakni
lingkungan yang mendukung, kolaborasi lintas disiplin, serta ketersediaan dana
dan waktu untuk mengejar ide-ide baru. Inovasi bukanlah produk pemikiran dari
seorang individu semata, melainkan dari ekosistem. Jika kita ingin menumbuhkan
lebih banyak penemuan tak terduga, maka yang harus dibangun bukan hanya
kapasitas individu, tetapi juga ruang kolaboratif yang cair, terbuka, dan
lintas batas.
Mengelola yang Tak Terkelola
Serendipitas bukan pengganti metode,
tetapi pengingat bahwa metode yang baik pun harus membuka ruang akan adanya kejutan.
Dan seperti yang dicontohkan Merton, penemuan yang paling jitu bukan selalu berupa
teori besar, namun dapat berupa konsep kecil yang mencerahkan. Di situlah
kekuatan sains yang sebenarnya.
Serendipitas memang paradox, ia tak bisa direncanakan, tapi bisa diciptakan
kondisinya. Ia tak bisa dipaksa muncul, tapi bisa dipupuk lewat pola pikir yang
terbuka, sistem yang fleksibel, dan keberanian untuk bertanya saat menemukan
hal aneh dalam experiment.
Di tengah era yang semakin terdikte oleh angka, prediksi, dan efisiensi,
mungkin sudah waktunya kita beri tempat bagi yang tak terduga. Karena dalam
banyak hal, sains berkembang bukan karena kita tahu ke mana harus pergi, tetapi
justru karena kita tersandung sesuatu yang membuat kita bertanya mengapa?.
Referensi:
- Campa, R. (2008). Making science by serendipity. Journal of Evolution and Technology, 17. Retrieved from https://jetpress.org/v17/campa.htm
- Ross, W., Copeland, S., & Firestein, S. (2024). Serendipity in scientific research. Journal of Trial & Error. https://doi.org/10.36850/v91j-7541
- Pyung, S., Lee, M., Zhang, Y., & Chen, H. (2025). Serendipity in science. Carlson School of Management & Boston University.